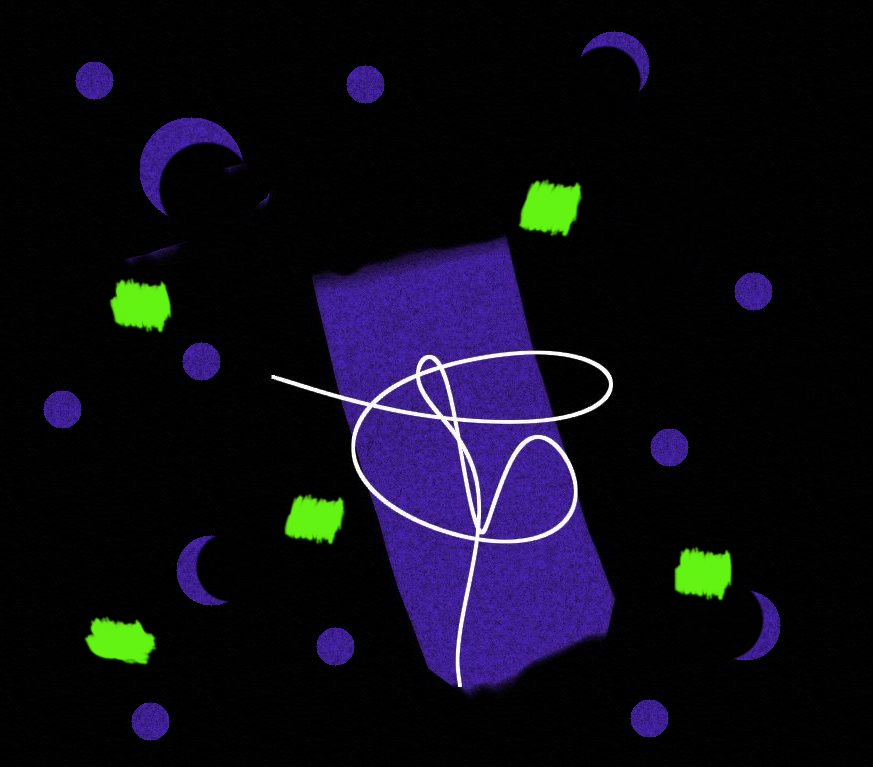tentang seseorang di malam turunnya kalam
ia kedinginan malam itu
embun turun di atas daun-daun
dan angin menyapu kelam dalam-dalam
baju katun yang dikenakan seolah menolak sunyi nun lamur
waktu seraya berhenti tepat pada saat imsak
ia tak berselimut
hawa dingin menelusup sendi-sendi tulang
tiada yang tahu jibril datang malam itu
sembari membawa kalam
wahyu, barangkali.
di atas daun ia berdiri
bajunya juga berbahan katun, barangkali.
adakah kau mendengar langkah kedatangannya dan
kepak sayapnya yang putih bersih bagai usai dicuci embun firdausi.
waktu yang purba hampir mendekati subuh
ia belum beranjak
gumam tasbih-tahmid-takbir ia zikirkan tanpa henti, seumpama mantra
mukanya berair
ia tak sendiri malam itu, ternyata.
ia menggigil
sosok bersayap itu membimbing, “bacalah!””
kali pertama. ia takut.
“bacalah!”
kali kedua. ia berselimut.
“bacalah!”
kali ketiga. ia terbata.
ia membaca dirinya.
ia membaca kaumnya.
ia membaca tuhannya.
iqra
ketika kau tak perlu menguji kata-kata yang tegak di hadapan sajak
yang bersanding dengan tanda-tanda bahasa—sesungguhnya
kau hanya perlu mendudukkan konteks pada koteksnya
sambil kaureguk madu makna yang sebenarnya.
jangan dulu mencintai hujan yang belum datang,
sebab kau baru saja belajar mendengar ricik
dan menyibak genangan air di sebuah ceruk.
jangan harap kautemukan jantung kata
dalam belanga bahasa,
meski kauselami darahku yang pekat
bercampur kesumba bercampur buah naga.
kau tak bisa mengeja puisiku yang
redup tergelapi mendung nan murung nurani.
mengertilah, aku merasa
berdosa membantumu melalar sajak-sajak buta,
yang membuatmu mengernyitkan dahi sehingga
kau merapuh lalu limbung bagai diberondong peluru.
sudah cukup perang kata-kata di media.
tak perlu kaugarami agar asin atau
kaugulai supaya manis.
tidaklah terang datang lantaran kautawarkan api hingga matahari.
cepat atau lambat, perang baru akan datang.
sebagaimana kauhapus jejakmu—
yang artinya memunculkan jejak baru.
ketika kau perlu menguji kata-kata yang tegak di hadapan sajak
yang bersanding dengan tanda-tanda bahasa—aku bersaksi,
sebenarnya,
tiap alir darahmu,
telah dipenuhi udara
untuk menyelami dalamnya inti kata.
di kafe
di kafe kudengar sayup-sayup waktu berwarna biru
sampai menggema di sekujur ruang tanpa peredam suara
angin laut berkejaran dengan daun-daun angsana
di luar. bukan sebuah simfoni turun dari langit tujuh
aku mengukur waktu yang tak menepi. sampai pada
sesapan pertama kopi yang dihidangkan seorang pelayan
pelan-pelan menarik jantungku tanpa sungkan
dan ampasnya melekat di bibir seolah ingin bercerita
kehilangan adalah udara yang gagal ditangkap pancaindra
sementara keheningan ibarat orkestra tanpa suara
yang partiturnya menjauh ke kedalaman samudra
kusempurnakan ritual minum kopi di kafe tanpa suara
waktu yang biru berangsur putih mengusik mata
dari jauh, kutemukan getir aroma kehidupan di atas keranda.